Pengelolaan kesejahteraan bukan hanya persoalan manajerial yang menyangkut “metode” pengelolaan dan sistem pendistribusian, melainkan juga persoalan politik yang membutuhkan partisispasi luas dari masyarakat secara substantif dalam keseluruhan proses pembuatan keputusan yang terbuka dan luas.
Beberapa
dekade terakhir, masalah sosial kronis, yaitu masalah kemiskinan, pendidikan,
kesehatan dan pengangguran mengalami sinergi yang amat berbahaya sebagai akibat
dari kesalahan orientasi pembangunan.
Dengan demikian akan menimbulkan permasalahan yang rumit ketika terjadi lingkaran setan kemiskinan, rendahnya pendidikan, hilangnya kesempatan bekerja, meningkatnya pelanggan tunjangan sosial, dan pupusnya motivasi dalam diri anak-anak muda untuk berkreasi. Muncul pertanyaan: siapakah yang berkewajiban menyelesaikan problem kronis ini?
Dengan demikian akan menimbulkan permasalahan yang rumit ketika terjadi lingkaran setan kemiskinan, rendahnya pendidikan, hilangnya kesempatan bekerja, meningkatnya pelanggan tunjangan sosial, dan pupusnya motivasi dalam diri anak-anak muda untuk berkreasi. Muncul pertanyaan: siapakah yang berkewajiban menyelesaikan problem kronis ini?
Pada dasarnya
masyarakat sangat merindukan kehadiran negara yang kuat, yaitu negara yang
mampu memenuhi kebutuhan publik. Namun hal itu tidak sejalan dengan percepatan
reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang demokratis, sehingga
seolah-olah negara tampak begitu lemah dalam merespon tuntutan dasariah
masyarakat.
Padahal, seturut
teori negara (kesejahteraan), negara dituntut
sebagai lembaga atau institusi yang dapat menjamin kesejahteraan rakyatnya (Bdk.
Madung, 2013: 79-86). Tuntutan inilah yang merupakan esensi dari demokrasi,
yaitu ketika terciptanya sebuah iklim yang memberikan peluang dan akses bagi masyarakat
untuk mengelola segala persediaan sumber daya, dan kemudian memanfaatkannya
untuk kebaikan taraf hidupnya.
Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma demokrasi dari sekedar kebebasan dan pemenuhan hak-hak politik menjadi kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma demokrasi dari sekedar kebebasan dan pemenuhan hak-hak politik menjadi kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Bersamaan
dengan perubahan tersebut, ranah demokratisasi pun mengalami pergeseran, dari
yang semua berlangsung di ranah masyarakat, tetapi kemudian beralih ke dalam
ranah pemerintahan. Perubahan paradigma demokrasi tersebut seiring dengan hasil
survei PWD-Demos (Paskarina, dkk., 2015)
yang menyatakan bahwa isu yang paling penting bagi publik adalah terkait
pemenuhan kebutuhan dasar dan keamanan.
Kemunculan
isu pelayanan publik dalam wacana demokrasi menyiratkan sisi lain dari praktik
demokrasi yang diabaikan oleh pemikiran mainstream,
yaitu kebutuhan untuk mengarahkan demokrasi pada masalah-masalah kesejahteraan
warga (Samadhi, 2016: 61-62; Savirani, 2016: 21-35).
Namun
persoalan utama dari demokrasi adalah menjamin agar masyarakat dapat melakukan
kontrol atas pembuatan kebijakan/keputusan publik, termasuk di dalamnya
mengontrol para pembuat kebijakan.
Dalam tataran
ini, hal terpenting adalah kapasitas kontrol rakyat atas kebijakan tersebut.
Hal itu tidak hanya menunjukkan hak politik warga, melainkan juga menjadi
penentu bekerjanya sebuah budaya demokrasi.
Dengan
menempatkan demokrasi dalam kerangka sebagai “kontrol popular dan persamaan
politik” (Beetham dan Boyle, 2000: 20), maka pengelolaan kesejahteraan pun
tunduk pada kontrol dan persamaan tersebut.
Itu berarti,
pengelolaan kesejahteraan bukan hanya persoalan manajerial yang menyangkut
“metode” pengelolaan dan sistem pendistribusian, melainkan juga persoalan
politik yang membutuhkan partisispasi luas dari masyarakat secara substantif
dalam keseluruhan proses pembuatan keputusan yang terbuka dan luas. Itulah
prinsip utama demokrasi, yaitu ketika keputusan diuji lewat tahapan
verifikasi dan revisi di ruang
publik.
Di titik
inilah politik diskursus menciptakan batasan-batasan normatif untuk memberikan
kriteria-kriteria tentang bagaimana pengelolaan kesejahteraan yang demokratis,
yang mengandung di dalamnya nilai-nilai partisipasi, akuntabilitas, penegakan
hukum, transparansi, egaliter, dsb.
Tentu,
pembatasan tersebut merupakan sebuah fondasi yuridis yang menjamin tercapainya
kebijakan publik terkait kesejahteraan publik. Pembatasan tersebut, dalam hal
ini hukum, dibuat untuk mengurangi kecenderungan bias pemaknaan dan monopoli
kekuasaan di tingkat lokal.
Tetapi kontrol
atas pengelolaan tersebut, selain oleh masyarakat, dalam dinamika politik
elit/pemimpin, hal itu merupakan pertarungan dari beragam institusi yang dapat
dipakai untuk mengakses dan mendistribusikan sumber-sumber daya tersebut kepada
rakyat, antara lain melalui lembaga negara, pasar, dan masyarakat warga.
Sebuah survei
oleh PWD (2007), misalnya,
menggarisbawahi pentingnya membuat demokrasi agar lebih bermakna dan bukan
sekedar berfokus pada pembenahan norma, institusi dan metode demokrasi; demokrasi
bukan hanya soal alat atau cara, tetapi juga tujuan.
Dengan
pergeseran tersebut, wacana kesejahteraan mulai muncul sebagai bentuk jawaban
kerinduan masyarakat melalui kinerja para aktor politik yang menggunakan jalan
pintas populisme. Populisme dilihat sebagai “pilihan terbaik” untuk mewujudkan
persoalan kesejahteraan (Olle Tornquist, 2015: 764).
Sebagai
strategi untuk mewujudkan negara kesejahteraan, populisme mesti berlagak dalam
koridor negara hukum demokratis. Selain untuk menunjukkan kehadiran negara-kuat,
populisme juga seharusnya bergerak di arena atau jaringan diskursus publik agar
elemen-elemen dan nilai-nilai demokrasi berfungsi secara baik. Itulah konsep
sederahana dari negara kesjahteraan (welfare state).
Dalam tataran
analisis lebih komprehensif, negara kesejahteraan adalah gambaran dari negara
demokratis yang secara konstitusional tidak hanya menjamin hak-hak dasar dan
kebebasan individual serta kebebasan ekonomi sebuah negara hukum, tetapi juga
mengambil langkah hukum, finansial dan material untuk menyelaraskan perbedaan
sosial, dan dalam batas tertentu, ketegangan dalam masyarakat. Karenanya, ada hubungan tidak terpisahkan antara
demokrasi dan negara kesejahteraan.
Negara kesejahteraan dalam konteks tertentu, tidak hanya bersikap rehabilitatif, tetapi mesti hadir sebagai kekuatan yang mencegah kesenjangan sosial, sejak
awal dan secara intensif membangun pendidikan berkualitas tinggi, serta
upaya-upaya preventif dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
Jadi, pada dasarnya konsep negara kesejahteraan merupakan sebuah “proyek”
atau “rekayasa” yang komprehensif dan berkualitas, yang tidak serta merta dapat
diwujudkan dalam waktu yang singkat, melainkan membutuhkan sebuah proses dan
arah yang jelas, entah itu terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang
teratur demi pencapaiannya di masa depan (Petring, dkk., 2012: 10-12).
Banyak
perdebatan terjadi
seputar wacana negara kesejahteraan yang berkisar pada masalah biaya, dengan
asumsi dasar bahwa kebijakan sosial, misalnya program KIP, KIS, dan KKH, menghambat
pertumbuhan ekonomi.
Padahal
demokrasi bukanlah soal “harga” (biaya), tetapi secara substantif lebih
merupakan sebuah “kebebasan”. Karenanya kebebasan dan pertumbuhan ekonomi tidak
dapat dipaksakan dalam sebuah timbangan yang sama.
Sebenarnya
mempertanyakan pembiayaan negara kesejahteraan pertama-tama mengacu kepada
kritik populer terkait redistribusi.
Secara umum,
redistribusi berarti mereka yang memiliki banyak memberi sebagian, dan mereka
yang memiliki sedikit memperoleh sebagian. Cara-cara atau kebijakan seperti ini
kadang-kadang dilihat sebagai “pembajakan” hak milik pribadi.
Namun
kebijakan tersebut tidaklah berarti negara mengabaikan hak milik warganegara,
tetapi persoalan hak-hak kepemilikan tidaklah berarti tanpa sebuah negara hukum
demokratis.
Karenanya
negara secara leluasa, di bawah payung hukum tertentu, mengintervensi warganya
dalam hal pemerataan. Intervensi negara melalui pajak dan penerimaan dari pasar
demi pemerataan adalah cara terbaik untuk memastikan kebebasan, keamanan dan
kepemilikan semua warganegara.
Oleh karena
itu, kebijakan sosial dan redistribusi bukanlah penyitaan hak-hak, melainkan
mesti diakui bahwa dalam menikmati kebebasan, ada sebagian warganegara yang
belum mampu memperolehnya.
Seperti terjadi
di negara-negara kesejahteraan Eropa, Indonesia pun secara progresif
mengembangkan konsep tersebut. Salah satunya adalah
kebijakan pemerataan harga BBM di Papua dengan harga di Jawa (Kompas, 14 November 2016). Hal
itu dimaksudkan agar setiap warganegara dapat memperoleh penghidupan yang layak
dan bermartabat.
Survei yang
dilakukan Kompas (2015), misalnya,
mengungkapkan tanggapan positif masyarakat terhadap kebijakan jaminan sosial
negara. Apa yang disebut sebagai “Kartu Sakti” Jokowi, yaitu KIP, KIS, dan KKH,
ternyata mampu menyokong kehidupan masyarakat kecil dan yang tidak mampu.
Meski demikian
program-program populis dalam sebuah negara kesejahteraan terkesan “memanjakan”
warganegara. Warganegara seolah tidak memiliki kemandirian hidup.
Karena itu
perlu memberdayakan rakyat agar mereka tidak “pasif”. Sebab sebuah
kesejahteraan yang efektif mesti menyertakan para penerima di dalam kewajiban-kewajiban
umum warganegara.
Tetapi karena
hak warganegara mesti didahulukan sebelum kewajiban-kewajiban, maka agaknya
tetaplah tidak ada perubahan berarti karena negara bertanggung jawab terhadap
hak-hak warganya.
Menyikapi
keambiguan ini, maka pentinglah mendemokratisasikan negara kesejahteraan.
Caranya adalah negara memberi agen-agen kesejahteraan setempat (rakyat
pedesaan) lebih banyak kekuasaan dan membuat mereka bertanggung jawab kepada negara.
Selanjutnya
negara melengkapi hak-hak atas kesejahteraan dengan hak-hak partisipasi
demokratis dalam pengelolaan program-program kesejahteraan. Program Dana Desa
yang digalakkan Jokowi merujuk kepada upaya demokratisasi kesejahteraan dengan
melibatkan perangkat negara paling bawah, yaitu desa.
Hal terpenting
dari program tersebut adalah bagaimana menggenjot aparat desa untuk benar-benar
melayani warganya, sambil membuka saluran-saluran politik warga dalam upaya
demokratisasi kesejahteraan tersebut.
Dengan
demikian, program tersebut dapat berjalan baik dan proses demokratisasi akar
rumput pun mengalami progresivitas.*
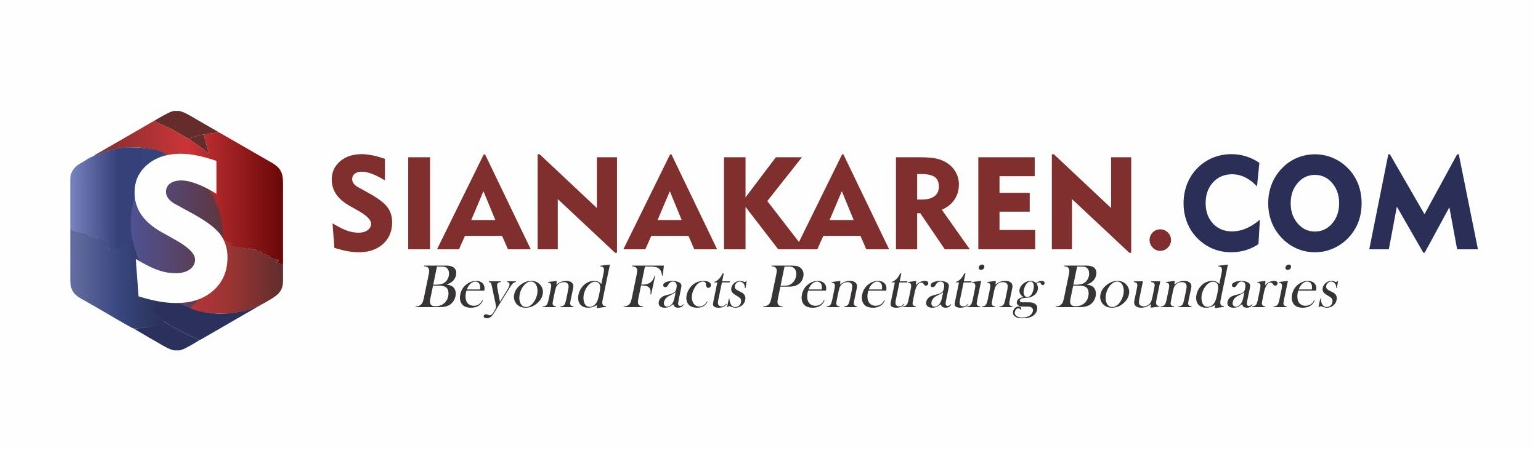












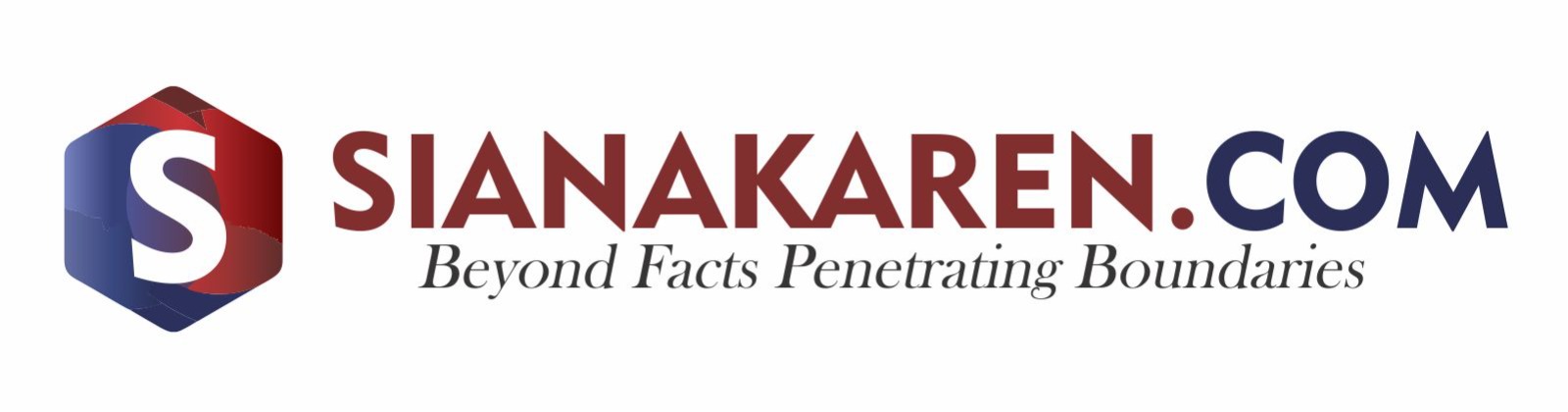
COMMENTS