Retorika post-truth adalah bentuk komunikasi di mana argumen dan pernyataan tidak lagi berfokus pada fakta objektif, realita, dan kebenaran universal.
SIANAKAREN.COM -- Kebangkitan populisme sayap kanan di sejumlah negara, antara lain di AS dan Eropa, muncul hampir bersamaan dengan era “post-truth” yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi.
Artinya, media dan teknologi informasi menjadi wadah atau ruang baru yang memberi keleluasaan bagi aktor politik populis untuk menjual retorika politik kepada pendukungnya di mana distribusi pesannya terbantu oleh algoritma media baru.
Ada beberapa karakteristik media baru, yakni network, interactivity, information, interface, archive, dan simulation (Nasrullah, 2014:14). Karakteristik tersebut pada gilirannya mengubah perilaku khalayak.
Di era digital, Cesaro (2011:403) menyebut khalayak bisa menjadi konsumer sekaligus produsen informasi (prosumer) (Nasrullah, 2014:63).
Lantas, seluruh elemen kehidupan sosial telah beresonansi dengan lingkungan media baru, bahkan media sosial bertindak dominan. Tidak lagi mengherankan pengaruh munculnya internet dan platform media sosial yang beragam membuat penyebaran berita palsu semakin intensif (Bhaskaran, Mishra, dan Nair, 2017:42).
Elit politik di beberapa penjuru dunia yang menggunakan wahana media sosial untuk memanipulasi paradigma masyarakat melalui fakta alternatif ataupun gosip jahat tentang lawan dengan asumsi sedikit bukti mendorong penyebaran kebodohan (Block, 2019:60).
Chadwick (Block dan Negrine, 2017:180) memandang gaya komunikasi populis terletak di era di mana politik ditengahi dan ditandai dengan meningkatnya kompleksitas dan fluiditas media.
Suwignyo (2019:xiv) menegaskan bahwa proses kerja politik “post-truth” difasilitasi oleh kehadiran teknologi informasi berupa media digital.
“Post-truth” menurutnya, pada akhirnya menandai benturan peradaban yang kian masif dan memincu sejumlah permasalahan baru tentang politik dan informasi. Inilah yang kemudian disebut sebagai era ‘politik informasi’, era di mana rezim politik bertindak dominan dan memonopoli produksi dan distribusi informasi.
Menurut Castells (1997:311-322), teknologi informasi telah memasukkan berbagai aturan baru dalam konteks transformasi sosial budaya, yang secara signifikan berpengaruh pada substansi politik. Media mampu menjadi bagian dalam ruang politik.
Politik secara tidak langsung telah terbingkai dalam hal substansi, organisasi, proses dan kepemimpinan, dengan logika yang melekat pada sistem media terutama media elektronik (Wuryanta, 2018:5).
Castells (1997:341) menyatakan di satu sisi media menjadi dasar bagi perebutan kekuasaan, namun di sisi lain politik media menjadi operasi kelembagaan yang semakin mahal yang menuntut aktor politik harus mencari dukungan finansial sehingga dapat terjebak ke dalam praktik korupsi.
Bagi Castells dalam masyarakat jejaring, informasi menjadi konten yang dipertukarkan antara pengguna media siber yan tidak berada dalam pemilihan antar pengirim dan penerima. Entitas memiliki peran ganda sebagai konsumen informasi sekaligus produsen informasi. Bahkan dalam kanal komunikasi yang semakin beragam, pengguna media telah menjelma menjadi audiens yang kreatif.
Sekitar satu dekade lalu, Toffler telah memprediksi gonjang-ganjing dunia bisnis. Dalam ketiga bukunya: Future Shock (1970), The Third Wave (1980), dan Power Shift (1990), Tofller memprediksi perubahan lanskap bisnis global akibat adanya revolusi digital dan revolusi komunikasi.
Dalam ranah pemasaran, perkembangan teknologi telah menghasilkan perubahan besar pada struktur komsumsi, pasar, dan dunia pemasaran. Proses ini digambarkan Cristensen (1997) bahwa inovasi teknologi informasi telah mengganggu atau menggantikan inovasi-inovasi sebelumnya.
Rhenald Kasali menyebutnya sebagai era disrupsi, ketika perusahaan teknologi seperti Facebook sejatinya mengganggu kemapanan media arus utama dengan platformnya (Syuhada, 2017:76).
Tsunami informasi ini menghadirkan sejumlah dampak sosial, bukan pada bagaimana mendapatkan berita, melainkan kurangnya kemampuan mencerna informasi yang benar. Kredibilitas media arus utama yang cenderung digerogoti kepentingan elit dan pemilik, memaksa masyarakat mencari informasi alternatif.
Sayangnya, media alternatif tidak selalu menghadirkan berita yang benar. White (Syuhada, 2017) menyinggung peran media baru Facebook dalam produksi dan peredaran informasi di era “post-truth”.
Dia mengkhawatirkan benturan yang bakal muncul akibat sirkulasi berita pelintiran dan informasi palsu yang beredar dan menyebar cepat di Facebook.
Setidaknya ada empat jenis informasi yang terdistribusikan dalam momen retorika politik “post-truth” di Facebook: fake news, hoax, hate speech, dan filter bubble.
Fake news adalah berita bohong, berita buatan atau berita palsu yang sama sekali tidak berlandaskan fakta, kenyataan atau kebenaran. Frasa ini bukan hal baru.
Pada awal 1835, New York Sun menerbitkan berita yang mengklaim ada kehidupan di Bulan. Pada 1844, beberapa surat kabar di Philadelphia menerbitkan laporan palsu tentang orang Irlandia yang mencuri Alkitab dari sekolah umum yang menyebabkan kerusuhan (Glasser, 2016).
Satu-satu perbedaan antara fake news masalalu dengan saat ini adalah kecepatan seiring penetrasi internet serta berbagai platform media sosial. Ball (2016) memberikan penjelasan mengenai wujud-wujud fake news.
Pertama, kesalahan pelaporan yang tidak disengaja. Kedua, rumor yang tidak berasal dari artikel berita tertentu. Ketiga, teori konspirasi yang sulit untuk diverifikasi sebagai informasi benar atau salah. Biasanya berasal dari orang-orang yang percaya mereka benar. Keempat, berita satire yang disalahartikan sebagai informasi faktual. Kelima, pernyataan palsu politikus. Keenam, laporan miring atau menyesatkan meski tidak langsung salah, atau sebagai distorsi.
Berbeda dengan fake news, hoax justru berupa informasi palsu, namun bisa berisi fakta yang telah dipelintir atau direkayasa. Hoax melekat sebagai atribut fitnah yang digunakan untuk menjatuhan lawan politik. Namun secara genealogis kata hoax tidak dimaksudkan demikian.
Menurut Nares (1753-1829), kata hoax mulai dipakai di Inggris pada abad ke-18. Nares menulis bahwa hoax berasal dari hocus, sebuah kata Latin yang merujuk pada hocus pocus. Pada lema kata hocus, Nares membubuhkan arti “to cheat” atau “menipu”. Hocus pocus mengacu pada mantra para penyihir yang kemudian dipakai para pesulap ketika memulai trik. Hocus pocus diambil dari nama penyihir Italia terkenal, yakni Ochus Bochus.
Thomas Ady, fisikawan Inggris abad ke-17, menjadi sumber yang lebih tua tentang asal frasa hocus pocus. Dari penelaahan Ady diketahui bahwa pada 1656 hocus pocus adalah mantra para penyihir yang tak berarti apa-apa. Seluruh pengertian hoax sejak Nares hingga Ady berujung pada kesimpulan bahwa hoax adalah “kabar bohong yang dibuat untuk melucu” atau sengaja membingungkan penerima informasi dengan maksud bercanda (Syuhada, 2017).
Sementara hate speech adalah seni dalam istilah hukum dan teori politik, yang mengacu pada perilaku verbal dan tindakan simbolis atau kegiatan komunikatif lainnya yang dengan sengaja mengekspresikan tindakan antipati terhadap kelompok maupun individu (Corlett & Francescotti, 2002:1083).
Kelompok yang dibenci dalam kasus ini biasanya didasarkan atas perbedaan etnis, agama, dan orientasi seksual. Hate speech menimbulkan masalah yang kompleks tidak hanya bagi demokrasi tetapi juga hak asasi manusia (HAM).
Fake news, hoax dan hate speech menjadi masalah penting di Facebook dan media sosial pada umumnya. Namun dampak buruk ketiganya akan meningkat berkali lipat dan dapat menyasar orang yang tepat karena adanya efek filter bubble (Pariser, 2011).
Algoritma ini diciptakan untuk memudahkan pencarian di Facebook di mana jejak digital pengguna Facebook dapat menyebabkan seseorang terisolasi secara intelektual di dunia maya karena Facebook menyingkirkan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan mindset penggunananya. Filter buble merupakan faktor penting dalam produksi fake news, hoax dan hate speech.
Kemenangan Trump pada Pilpres AS 2016 merupakan strategi kampanye yang menggunakan media baru sebagai basis distribusi pesan (Jatmiko, 2019:21). Lewat retorika “post-truth” di Facebook, Trump membentuk opini publik seturut logika emosi dan keyakinan personal rakyat Amerika (Golose, 2019:8).
Dalam situasi itu, informasi-informasi hoaks berpengaruh lebih besar ketimbang fakta. Faktanya, selama Pilpres AS 2016, semakin sering media menyiarkan berita-berita bohong mengenai Trump, justru membuat nama sang mestro real-estate AS itu semakin populer dan kebohongannya tersebar luas.
Dalam retorika, ada istilah bandwagon, yaitu klaim kebenaran hanya karena suatu pernyataan itu populer, atau meminjam istilah Harsin (2018) sebagai “emo-truth.
Basis tulisan ini merujuk pada argumentasi McComiskey (2017:3), yang menganalisis fakta kemenangan Trump karena retorika “post-truth”.
Menurut McComiskey, kemenangan Trump sebagai presiden ke-45 tidak dilakukan dengan cara biasa. Artinya, tidak hanya menggunakan argumentasi yang tulus dan persuasi etis untuk menunjukkan bahwa ia memiliki pengalaman yang paling relevan dan rencana terbaik untuk membesarkan kembali AS.
Sebaliknya, Trump memenangkan pemilihan menggunakan strategi retorika yang tidak etis seperti berita palsu, publikasi media sosial yang palsu, pembalikan kebijakan, penolakan makna, serangan terhadap kredibilitas media, dan sebagainya.
Semua ini merupakan bentuk strategi retorika tidak etis, yang mana terus-menerus disiarkan televisi dan diulangi selama setahun masa kampanye dan siklus pemilu, dan telah sangat mempengaruhi wacana publik. Populisme “post-truth” telah mendapatkan tempatnya yang strategis di tengah tsunami informasi.
Menurut McComiskey (2017:7), kampanye dan pemilihan Trump mewakili momen retorika yang menentukan dalam dua cara: pertama, telah terjadi perubahan dalam cara orang-orang kuat menggunakan retorika yang tidak etis untuk mencapai tujuan mereka; dan, kedua, telah terjadi pergeseran bahwa khalayak publik mengkonsumsi retorika yang tidak etis.
Padahal dalam bentuknya yang paling kuat, retorika berurusan dengan argumentasi yang sahih dan rasional. Gagasan argumen rasional membutuhkan fakta, realitas, dan kebenaran sebagai referensi dan standar yang dengannya dapat dibandingkan. Semua retorika hingga baru-baru ini telah ada pada kontinum epistemologis yang mencakup fakta-fakta tertentu, dasar realitas, dan kebenaran universal, bahkan ketika retorika itu tidak berpartisipasi dalam fakta, realitas, dan kebenaran.
McComiskey menandaskan, bentuk-bentuk kampanye negatif, dengan kata lain populisme “post-truth” Trump, dinyatakan salah dan merupakan strategi retorika tidak etis karena ketiganya tidak dapat dibandingkan kebenaran universal. Di dunia “post-truth”, bahasa menjadi murni strategis, tanpa referensi untuk apapun selain dari dirinya sendiri.
Pada akhirnya, retorika aktor politik populis “post-truth” menurut Tallis (2016) bertujuan untuk melakukan “destabilisasi atau bahkan penghancuran gagasan tentang kebenaran. Kemenangan Trump menjadi bukti masivitas lanskap politik “post-truth” saat ini (Marcus 2016:A17).
Pada akhirnya, ungkapan fakta alternatif mulai diciptakan pada tahun 2017 sehingga menjadi slogan populer di beberapa negara negara, khususnya Eropa dan Amerika, termasuk Indonesia pada Pilpres 2019.
Fakta alternatif digunakan untuk menggambarkan pernyataan yang diekspresikan baik dalam ketidaktahuan sepenuhnya atau dengan total mengabaikan kenyataan (Strong, 2017:1).
Ini dapat melumpuhkan narasi faktual, sebab narasi alternatif diklasifikasikan sebagai berita palsu karena tidak sesuai dengan pandangan mayoritas (Bhaskaran, Mishra, dan Nair, 2017:44). Inilah yang disebut era post-factual ketika kebenaran tidak lagi diletakkan pada fakta, tetapi narasi-narasi subyektif. Atau yang disebut Lippmann sebagai relativisme kebenaran (Wahyono, dkk, 2017:25).
Kebohongan tidak lagi hanya sebagai kebohongan yang mudah dipatahkan, akan tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah menjadi fakta alternatif yang dapat diterima oleh publik (Mair, 2017:3-4).
Dengan kata lain, klaim besar tentang era “post-truth” lainnya juga tidak berusaha membangun model realitas yang koheren; titik di mana fakta tidak lagi penting atau bahkan tidak diakui ada. Narasi alternatif yang secara faktual menyesatkan dapat melawan efek informasi faktual (McCright et al., 2016:76-97).
Satu metode penyebaran kebohongan secara masif dan sistemik adalah FoF. Metode ini bertujuan mencemari lingkungan informasi untuk mempengaruhi informasi yang tersedia bagi pembuat kebijakan atau mempengaruhi mereka melalui tekanan demokrasi atau untuk mengikis kepercayaan pada lembaga-lembaga pemerintah dan media dengan menyemburkan narasi palsu.
Seiring penetrasi internet, kontestasi politik di Indonesia tidak jauh dari fenomena “post-truth”. Bahkan pada Pilpres 2019, Prabowo serta merta mengadopsi gaya retorika “post-truth” yang dimainkan Trump pada Pilpres AS 2016.
Semburan kebencian yang dilancarkan kubu BPN Prabowo-Sandi terhadap petahana Jokowi begitu masif di jagat maya Indonesia.
Ada kejenuhan ketika masyarakat disuguhkan informasi-informasi bohong dan palsu, yang tidak saja muncul secara verbal, melainkan juga terbantu oleh algoritma media sosial.
Sebagai kesimpulan bahwa retorika post-truth adalah bentuk komunikasi di mana argumen dan pernyataan tidak lagi berfokus pada fakta objektif, realita, dan kebenaran universal, tetapi lebih pada penggugah imaji, emosi, dan kepercayaan pribadi audiens.
Retorika ini sering digunakan dalam konteks populisme kanan dan digital dakwah, terutama di ruang sosial dan politik. Inti dari retorika post-truth adalah bahwa logos (logika dan fakta) menjadi kurang penting dibandingkan dengan ethos (kredibilitas yang bisa asli atau palsu) dan pathos (emosi), serta adanya elemen yang disebut "bullshit" yang berarti misrepresentasi dan penyesatan yang diterima sebagai kebenaran oleh audiens.
Dalam era post-truth, kepedulian terhadap fakta dan kebenaran objektif cenderung hilang, dan opini publik lebih dipengaruhi oleh rayuan emosional dan kepercayaan pribadi daripada data atau bukti nyata. Hal ini menghasilkan disinformasi, hoaks, dan konflik sosial-politik yang kerap terkait dengan fanatisme dan antagonisme antara kelompok-kelompok tertentu.*
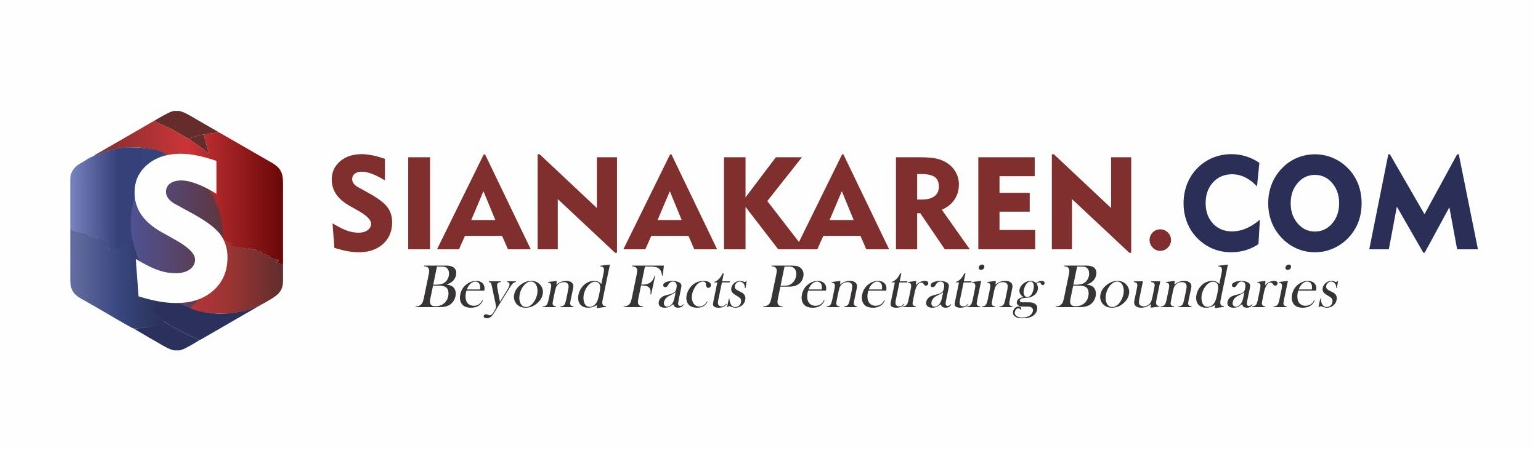












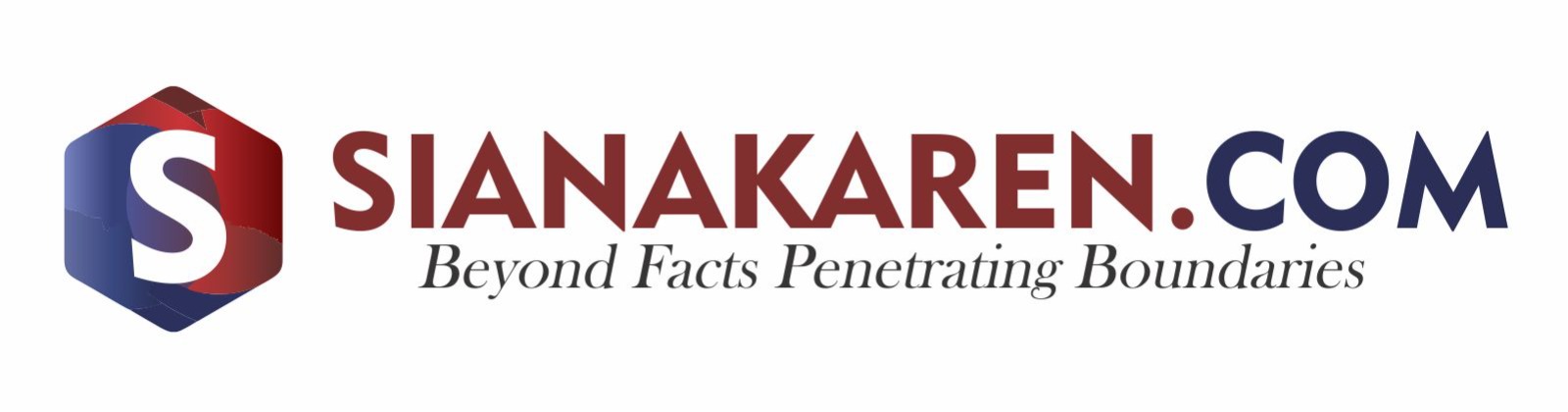
COMMENTS