Problematika keterlibatan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia mencakup tiga hal, yaitu: kurangnya minat perempuan terhadap politik; dominasi persepsi maskulinitas secara struktural kekuasaan, dan domestikasi peran sosial perempuan.
 |
| Ilustrasi basis konstitusional hak politik perempuan Indonesia. Kredit: psi.id |
Berpolitik layaknya
sebuah “seni”. Bila memang politik didefenisikan sebagai sebuah space untuk meraih kekuasaan, atau
dengan kata lain, politik identik dengan kekuasaan, maka menjadi lumrah jika
terminologi “seni” disematkan pada politik. Sebagai sebuah “seni” politik
bertujuan untuk
mencari dan mengkombinasi berbagai kemungkinan (potensi) untuk
mengarahkan masyarakat kepada sebuah cita-cita dasar dari
masyarakat itu sendiri (Budi Kelden, 2003).
Karena itu,
segala cara dilakukan atau dikerahkan agar representasi politik selalu menarik.
Itu tidak hanya pada batasan substansial politik, tapi juga menyentuh sepak
terjang aktor politik. Ketepersonaan pemilih untuk menentukan pilihan dalam
Pemilu/Pilkada, misalnya, ditentukan pula oleh sejauh mana daya tarik
aktor-aktor politik “bermain”. Ini fakta, dan bukan rekayasa.
Benar apa yang
dikatakan Hobbes, bahwa manusia-manusia
dapat melakukan apa saja atas manusia lain demi memenuhi hasrat dan kepentingan
primordialnya, dan ini mungkin menjadi hal yang sangat representatif dari aspirasi publik terhadap para aktor politik. Bilamana
dipandang dari perspektif pengertian politik sebagai
seni, maka dapatlah diaminkan kalau itu
merupakan bagian dari sebuah “seni” berpolitik.
Tidak terbatas dari
suatu ranah kehidupan sosial, politik mampu menjiwai segala aspek
dan mempunyai batasan-batasan khusus, seperti yang
diajukan oleh Lasswel (1972). Barangkali sangat representatif, bahwa politik
adalah urusan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana (who gets what, when dan how).
Apa yang dikatakan Lasswel sedikit jelas
dan relevan bahwa politik merupakan “urusan” seseorang (pemimpin) untuk
mendapatkan apa yang ia inginkan, kapan ia memperoleh keinginannya dan bagaimana ia mengkalkulasikan keuntungan.
Cara kerja
pragmatisme, utilitarianisme, dan produktivisme, adalah bentuk-bentuk
maskulinitas realitas politik. Itu terjadi sejak dahulu kala, bahwa politik
dibalut secara kental oleh unsur maskulinitas. Mengapa demikian? Karena
karakter maskulinitas cenderung berpikir dan bertindak inovatif, kreatif,
produktif, dan “menguasai”. Itulah mengapa politik itu identik dengan
“kekuasaan”.
Sementara itu, karakter
feminitas tidak pernah berkiblat. Itulah perbedaan sekaligus stereotipe klasik
yang terus dibawa hingga kini: ada pembedaan tegas antara laki-laki dan
perempuan. Bila perempuan tidak terlalu berpikir tentang apa, kapan, dan
bagaimana menginvestasi politik, laki-laki justru lebih elegan mengolah sirkus
politik lewat sebuah “drama” yang menakjubkan. Kelihatan mulia, luhur, dan
halal, tapi nyatanya mereka “bermain cantik” di air keruh. Lantas, bagaimana
nasib aspirasi (emansipasi) politik perempuan di Indonesia.
Terhitung sejak
Pemilu 2004, 2009 dan 2014, dan kini 2019, ketika demokrasi politik sedikit berubah haluan dengan label “Reformasi“, keterlibatan
figur perempuan menjadi sebuah kemendesakan (emergency). Pengaturan konstitusional hak politik perempuan mulai
dipertimbangkan.
Dalam pasal 7 Undang–Undang No. 31
Tahun 2002, menegaskan betapa pentingnya hak rekrutmen
dalam hal pengisian jabatan politik yang memperlihatkan kesetaraan gender. Memang istilah
gender akhir-akhir ini diperdebatkan karena sangat tendensius; ia lebih mengarah
kepada terminologi seksualitas ketimbang sosiologis.
Berdasarkan undang-undang tersebut sebenarnya setiap orang, tidak seperti praktik politik di polis Athena kuno, diberi
kebebasan yang luas untuk memilih dan
dipilih. Dengan kata lain, setiap warganegara punya hak untuk direkrut menjadi
pejabat politik apapun bentuknya.
Itulah esensi
demokrasi menurut David Beetham (1997): demokrasi menyangkut persamaan hak
politik warganegara. Karena politik adalah sebuah pilihan, artinya tidak bersifat imperatif, maka seseorang yang terjun ke dunia politik otomatis sudah
mafhum dengan urusan politik itu sendiri dan sudah siap
mengambil segala resiko terhadap pilihannya.
Undang-Undang No. 2
Tahun 2008 tentang Parpol dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu pun menggarisbawahi
satu poin penting mengenai keterlibatan perempuan dalam politik. Secara
eksplisit disebutkan bahwa kouta keterwakilan perempuan adalah 30 persen, atau
dengan kata lain, dalam sebuah parpol terdapat satu orang calon perempuan dari
tiga calon laki-laki.
Hal itu kemudian
berlanjut para soal kelayakan sebuah parpol untuk mengikuti Pemilu, di mana
parpol-parpol wajib memiliki keterwakilan 30 persen perempuan.
Ironisnya, yang terjadi sejauh ini adalah politisi
perempuan yang duduk di legislatif belum mencapai target kuota tersebut.
Fakta ini menafikan satu pertanyaan substansial:
mengapa calon perempuan begitu sulit menembus tiket untuk duduk di kursi
legislatif maupun jabatan politik tertentu? Apakah
perempuan adalah orang-orang lemah, tak berkuasa, dan mesti kehilangan hak-hak dasarnya di tengah gencarnya perjuangan gender
dan penyetaraan akses sosial? Bukankah produk
undang-undang ini secara implisit telah mengkerdilkan ruang partisipasi
perempuan dan mendiskreditkan peran perempuan sendiri?
Bahwa perempuan
dalam hal apapun tidak pernah bisa menyamakan diri dengan laki-laki adala martabat
kodrati. Namun
demikian, perempuan tetap diberi kesempatan untuk berdiri di bilik bebas dan tidak terpenjara oleh
kodrat
domestifikasinya sendiri.
Data yang diperoleh
dari KPU (Sindonews.com) menyebutkan
bahwa total DPT Pemilu 2014 adalah 186.612.255 pemilih, yang terdiri dari
93.439.610 pemilih laki-laki, dan 93.172.645 pemilih perempuan. Lalu Pemilu 2019
tahun ini bertambah dengan jumlah pemilih 192.828.520 orang, dengan rincian
96.271.476 laki-laki dan 96.557.044 perempuan.
Sepintas data ini
memperlihatkan dengan jernih bahwa pemilih perempuan dan laki-laki hampir
seimbang, atau malah perempuan unggul sebesar 26.714.432 orang. Artinya,
secara hak politik, perempuan memiliki porsi keterlibatan yang lebih dari
laki-laki.
Namun jika menyelisik
fakta diskriminasi hak politik kita saat ini, penulis menyimpulkan bahwa
perempuan Indonesia telah diracuni oleh jiwa maskulinitas politik. Mengapa?
Karena bisa saja kaum perempuan menyatukan suara untuk memilih calon-calon
perempuan, jika mereka telah sadar dan memahami prinsip egaliter sebagaimana
diperjuangkan selama ini.
Dengan demikian, pada Pemilu Legislatif 2019 kali
ini, kuota keterwakilan perempuan mencapai target, atau lebih. Atau
setidak-tidaknya menghasilkan politisi perempuan yang ‘benar-benar’ perempuan,
dan bukan berjiwa maskulin.
Pandangan umum tentang lemahnya
perempuan
dalam dunia politik sebenarnya hal yang absurd, karena politik pada dasarnya merupakan
pilihan hidup seseorang. Siapapun tidak memaksa atau mengintervensi pilihan
seseorang. Entah sampai kapan keterlibatan perempuan dalam politik memenuhi
kuota konstitusional, pemerintah sekalipun tidak bisa bersikap koersif terhadap
warganya.
Karena itu,
hemat penulis, problematika
keterlibatan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia mencakup tiga hal, yaitu: 1) kurangnya minat
perempuan terhadap politik, 2) dominasi
persepsi maskulinitas
secara struktural kekuasaan, dan 3) domestikasi peran sosial perempuan.
Pertama, boleh
jujur diakui bahwa pilihan perempuan terhadap politik sangatlah rendah/minim. Jika
ditanya, apa cita-cita kalian para perempuan? Jawabannya pasti ingin jadi
dokter, guru, perawat, pramugari, dst. Berbeda dengan laki-laki yang bila
ditanya pasti menjawab akan menjadi politisi, bupati, tentara, polisi, arsitek,
dst. Inilah wilayah problematika paling mendasar.
Kedua, tidak
jarang struktur kekuasaan selalu identik dengan “kekerasan” yang menimbulkan
rendahnya minat perempuan untuk “terjun” ke dalamnya. Dan ketiga, apapun pekerjaan perempuan pasti mereka tidak lupa akan
tugas utamanya, yaitu menjadi “ibu” dalam keluarga. Dengan itu, ketika menjabat
atau terlibat dalam aktivitas politik, ada kemungkinan besar untuk sekedar
mengurus “rumah tangga” politik.
Perempuan tak selamanya dilabelkan sebagai kaum yang
tidak dapat bergulat dalam bidang politik. Lantas, yang menjadi upaya dasar dari kita
adalah perempuan “harus” mampu berada pada bidang pilitik itu sendiri, karena
partisipasi politik adalah sikap yang mencakup segala hal yang mempunyai
relevansi politik ataupun hanya mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam
mengambil keputusan.
Semakin banyak
perempuan dalam proses pengambilan kebijakan, semakin baik dan adil kebijakan
tersebut. Mengapa? Karena ada perimbangan antara kekuatan maskulinitas dan
feminitas kebijakan politik. Contohnya, minimnya perempuan dalam pembuatan
kebijakan politik, menyebabkan produk kebijakan yang bias gender dan timpang.
Atau dalam kasus pelecehan seksual karyawan BPJS
yang mengemuka beberapa waktu lalu. Di hadapan produk kekuasaan, perempuan
tidak punya daya tawat politik, sehingga persoalan-persoalan perempuan meski
terus diperjuangkan di satu sisi, tapi tetap tumpul di area yang lain.
Karena itu,
mendesak dan penting, bahwa perempuan mesti terlibat penuh
di dalam desain
pembuatan kebijakan politik, sehingga ada porsi
keberimbangan perspektif,
psikologis dan rasionalitas kebijakan politik.*
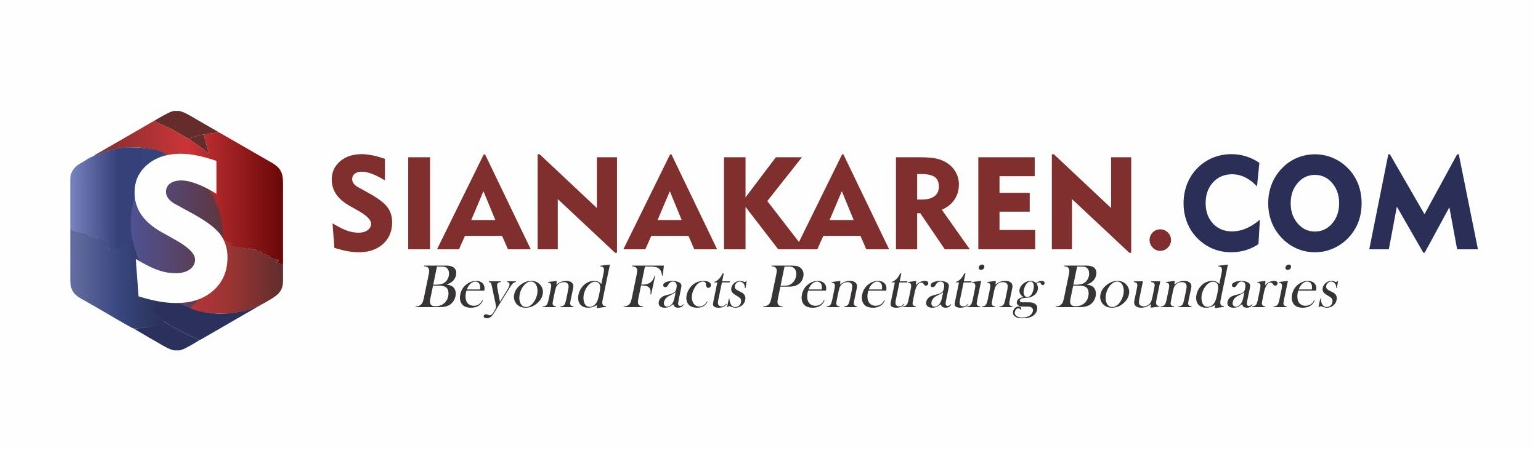











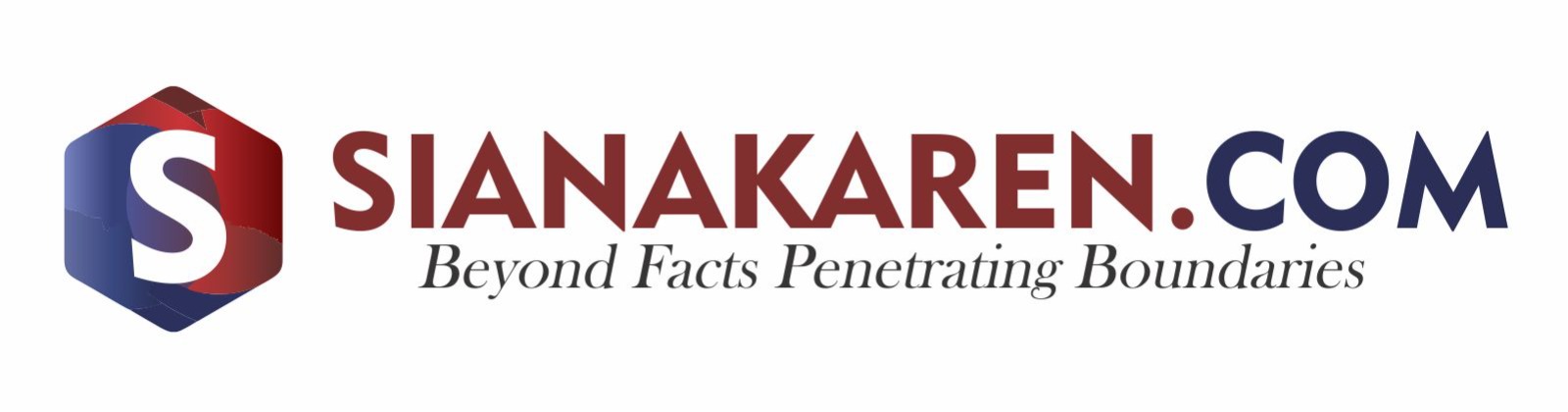
COMMENTS