Karya sastra NTT masih berkutat di lingkaran abu-abu; belum ada kekhasan yang mewakili budaya kita.
 |
| Ilustrasi karya seni. Kredit: Tribunnews.com |
Sedang kedudukan berimbang 1-1: Barca unggul lebih dahulu lewat sontekan cerdik Pedro Rodriguez (‘27) dan MU menyamakan kedudukan lewat striker andalannya, Wayne Rooney (‘34).
Di menit ke-54 tendangan kaki kiri sang “Messiah” tidak
mampu diantisipasi sang kiper. Tepat di sudut kiri gawang – titik lemah van der
Sar – Messi menyodorkan dengan amat cermat dan kedudukan berubah 3-1. Gelar
“The Messiah” yang dikenakan padanya seimbang dengan “ke-pahlawannya”
menghantar Barcelona merengkuh tropi juara Liga Champion tahun itu.
Ada sebuah cerita lain. Pada masa penjajahan di bumi
Indonesia, tampillah orang-orang kuat sekelas Diponegoro, Kapitan Pattimura,
Ngurah Rai, dll., yang membela tanah air dari serangan kolonialisme. Mereka kemudian
mati berkucuran darah setelah menjadi “pahlawan” di daerahnya masing-masing.
Di slide
yang lain ditayangkan pula cerita tentang kisah para “Pahlawan Revolusi” yang
mati terbunuh akibat kekejaman yang didalang oleh Partai Komunis Indonesia
(PKI) pada 1 Oktober 1965. Mereka adalah korban kejahatan lawan, namun mereka
dianggap “pahlawan” karena setia membela Pancasila.
Di lain pihak, kita mengenal adanya istilah
“pahlawan” devisa. Siapa lagi kalau bukan para pekerja luar negeri (TKI/TKW).
Mencari mencari sesuap nasi di negeri orang, namun beberapa persen dari penghasilan
mereka disetor ke pemerintah sebagai sumber devisa.
“Pahlawan” jenis ini tidak mengorbankan nyawa,
tetapi sebagai pekerja, mereka justru mengucurkan keringat seperti pekerja
lainnya.
Lain lagi halnya dengan cerita Soeharto yang dinilai
sebagai “pahlawan” Orde Baru karena telah mengangkat derajat manusia Indonesia
melalui visi pembangunan yang terencana dan berhasil baik.
Padahal, di sisi lain, Soeharto sedang menggali
“lubang hitam” yang memerosokan bangsa ke jaringan neoliberalisme. Ia juga
menyisakan noda sejarah yang hingga kini masih akut diperbincangkan, yaitu
utang luar negeri yang besar dan korupsi, sehingga banyak pihak menolak gelar
ke-pahlawanannya.
Dari beberapa kategori “ke-pahlawan-an” tersebut di
atas, kita tidak bisa mengafirmasikan kategori yang satu merupakan “pahlawan”
yang sebenarnya daripada kategori yang lain. Kelimanya sama-sama menampakan
diri sebagai “pahlawan” di masing-masing wilayah pengertian. Serentak, kategori-kategori
tersebut, bahkan bisa lebih, mengeksplisitasikan satu pertanyaan penting: apa dan
siapa itu “pahlawan”?
Sebagaimana dilansir dari
sumber tersedia, kata “pahlawan” berasal dari kata bahasa Sanskerta: phala-wan, yang berarti ‘orang yang dari dirinya menghasilkan
buah (phala) yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agama’. Mereka
adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam
membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan
berarti ‘orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela
kebenaran; pejuang yang gagah berani’. Pahlawan adalah seseorang yang berpahala
yang perbuatannya berhasil bagi kepentingan orang banyak. Perbuatannya memiliki
pengaruh terhadap tingkah laku orang lain, karena dinilai mulia dan bermanfaat
bagi kepentingan masyarakat bangsa atau umat.
Sejarawan
Anhar Gonggong (dilansir dari Merdeka.com) mengatakan gelar “pahlawan” tidak
bisa diganggu gugat. Makanya harus dipahami dulu apa itu “pahlawan” dan
“pemimpin”.
Menurutnya,
pemimpin kemudian menjadi pahlawan adalah orang mampu melampaui dirinya. Kalau
dia tidak mampu melampaui dirinya, dia tidak akan menjadi “pahlawan” dan tidak
bisa menjadi “pemimpin”. Bahkan dengan melampaui dirinya, sampai menyerahkan
nyawanya pada tindakan tertentu jika memang dianggap perlu.
Dari beberapa
pengertian ini kiranya terbersit secercah kejernihan intelektualitas kita
perihal pemahaman yang sejati apa dan siapa itu “pahlawan”. Bahwa “pahlawan”
bukan saja mereka yang gagah berani menentang penindasan, mengucurkan darah, berprestasi,
berhasil dalam kepemimpinan dan managerial, dsb., tetapi juga adalah mereka
orang-orang kecil, kaum sederhana, orang miskin dan kaum pinggiran, namun
kemudian memberi “sesuatu” untuk orang lain melalui karya, keutamaan dan
teladan hidup.
Hemat saya,
“pahlawan” sejati tidak mesti harus dilihat dari seberapa sumbangan ide,
pemikiran, prestasi, ataupun keberanian tertentu. “Pahlawan” sejati adalah
deretan orang-orang yang mau membaktikan hidupnya demi “sesuatu” yang “melampaui”
dirinya; ia selalu merasa dirinya lebih sempurna jika hidupnya diabdikan bagi
orang lain.
Seberapa
besar pengabdiannya tidak mesti diukur dalam neraca manusiawi. Sebaliknya, yang
dipakai adalah neraca ketulusan, totalitas, keutuhan dan integritas pribadi
dalam mengaktualisasikan dirinya demi sesuatu yang lebih berharga dari dirinya.
Sebagai akademisi muda, di manakah letak “kepahlawanan” kita?
Kiblat Kaum Muda
Tidak bisa
dinafikan bahwa bangsa ini berdiri di atas pundak intelektualis muda. Sebut
saja nama besar seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Moh. Yamin, Sutan Syahrir,
dll. (Walaupun Soeharto bukan termasuk angkatan ’45, namun ia juga adalah
pemimpin muda yang menakhodai bangsa ini selama 32 tahun).
Deretan nama para
“founding fathers” ini adalah para pemimpin bangsa yang ketika memimpin usianya
masih sangat relatif muda, yaitu sekitar 40-an tahun.
De facto,
usia mereka tidak menentukan sama sekali aneka kebijakan dalam membangun bangsa
ini. Dibekali oleh pendidikan yang memadai ala
Belanda, mereka adalah pejuang dan pendongkrak kedaulatan tanah air Nusantara.
Selama kurang lebih 50-an tahun hingga
1998, mereka bahkan menjadi tangguh, kuat dan bijaksana karena visi kemudaannya,
walau di sisi lain “lubang” ketidakadilan menganga.
Fakta lain
pun berbicara senada. Pada pertengahan tahun 1997-1998, ketika bangsa Indonesia
mengalami goncangan ekonomi yang hebat (krisis moneter), muncul sekumpulan kaum
muda, para akademisi dan intelektualis muda, mempertanyakan kebijakan ekonomi
nasional. Hingga akhirnya mereka berhasil menggulingkan pemerintahan otoriter Soeharto dan segala kebijakan didaur
ulang.
Wacana
reformasi bergaung, tanda menyeruaknya iklim kebebasan multidimensi. Kita
lihat, mereka yang berani bersuara di gedung-gedung pemerintah dan DPR kala itu
adalah para akademisi muda. Nyawa menjadi taruhan; hidup mereka tak lagi
dipikirkan. Mereka berjuang melawan “kejahatan”. Mereka adalah orang-orang
kecil, sederhana, tak diperhitungkan, namun berani berjuang mengentas
ketumpulan pemerintah yang diam dan membiarkan “kejahatan” berkelindan. Lantas, bagaimana dengan kita?
Sebagai
intelektualis muda yang hidup di zaman di mana segala sesuatu menjadi
“mungkin”, tuntutan mesti dikenakan lebih. Karena jika dulu orang menggali
lubang menggunakan tofa maka sekarang
kita telah dibantu oleh alat secanggih eskavator;
dulu orang berkomunikasi jarak jauh dengan pengantaraan kuda, sekarang kita
telah dibuai oleh teknologi digital, yang untuk berkomunikasi, jari-jari
tinggal menekan tombol “telepon” dan seketika dunia seberang menjadi begitu
dekat.
Kesejatian
“kepahlawanan” kaum muda justru terletak pada seberapa besar kualitas
pengabdian kita bagi yang lain: umat/masyarakat, negara dan bangsa. Apakah kita
bisa menjadi “pahlawan” bagi sesama dan komunitas kita? Pertanyaan lain:
Mengapa kita begitu lantang mengeritik “kejahatan” sistem, sedang kita sendiri
sebagai intelektualis muda, mengorbankan kehidupan dan masa muda kita demi
sebuah negativitas. Ironis.
Geliat Sastra
Tidak cukup
generasi muda sekarang mengenang kepahlawanan para “tetua” dulu hanya dengan
menulis kritikan konstruktif (makalah/opini) atau melakukan orasi politik.
Apakah sepadan “darah” yang dikucurkan demi tanah air dibalas dengan tulisan
dan pembicaraan semata?
Kita mesti
melakukan apa yang melampaui kebiasaan. Untuk kita di NTT, jarang ada karya
sastra yang menarasikan salah satu tokoh “pahlawan” wilayah kita, entah itu
Marilonga, Nipa Do, Tea Iku, Motang Rua, dll.
Karya sastra
kita masih berkutat di lingkaran abu-abu: belum ada kekhasan yang mewakili
budaya kita. Memang akhir-akhir ini sastra NTT tengah bergeliat. Tetapi itu
belum seberapa.
Hal ini terlihat
dari tidak seberapa produk sastra yang muncul. Saya menawarkan satu langkah
konkret yang bisa dibuat adalah dengan, tentu karena latar intelektual kita,
mendokumentasikan narasi kepahlawanan kita dalam karya sastra: entah cerpen,
puisi, novel, prosa, atau cerita rakyat, dengan gaya dan penyajian bahasa yang
komprehensif serta penyelidikan fakta yang akurat. Sehingga sastra kita bukan
sekedar karya fiksi, tetapi ditulis berdasarkan latar kehidupan budaya kita
sendiri.
Dengan itu
produk sastra kita bergerak dalam alur yang jelas dan khas.*
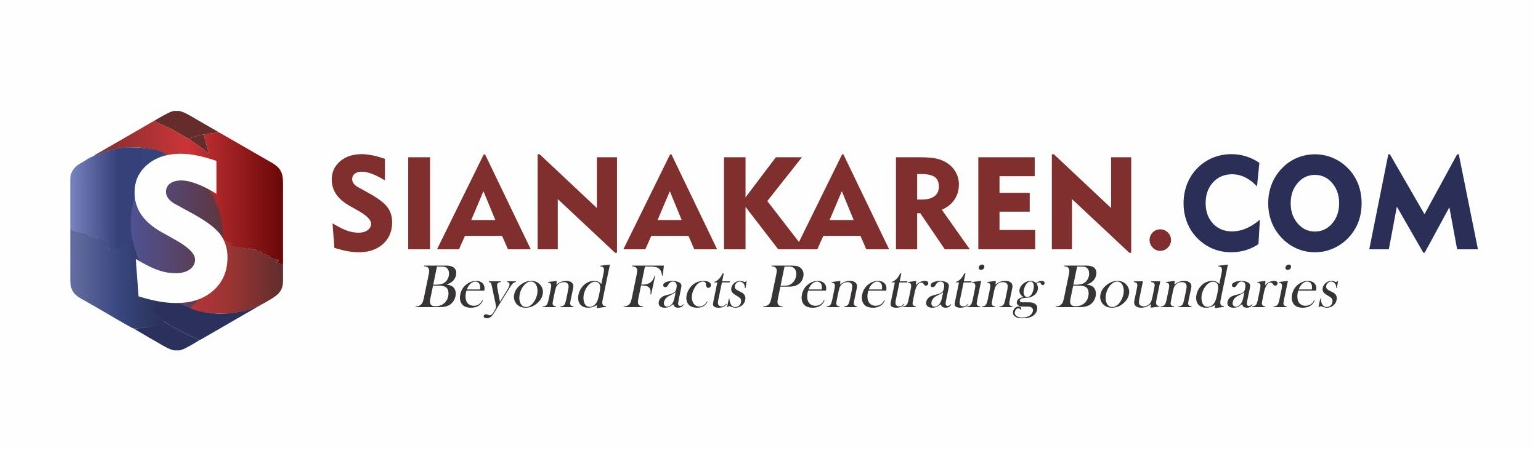











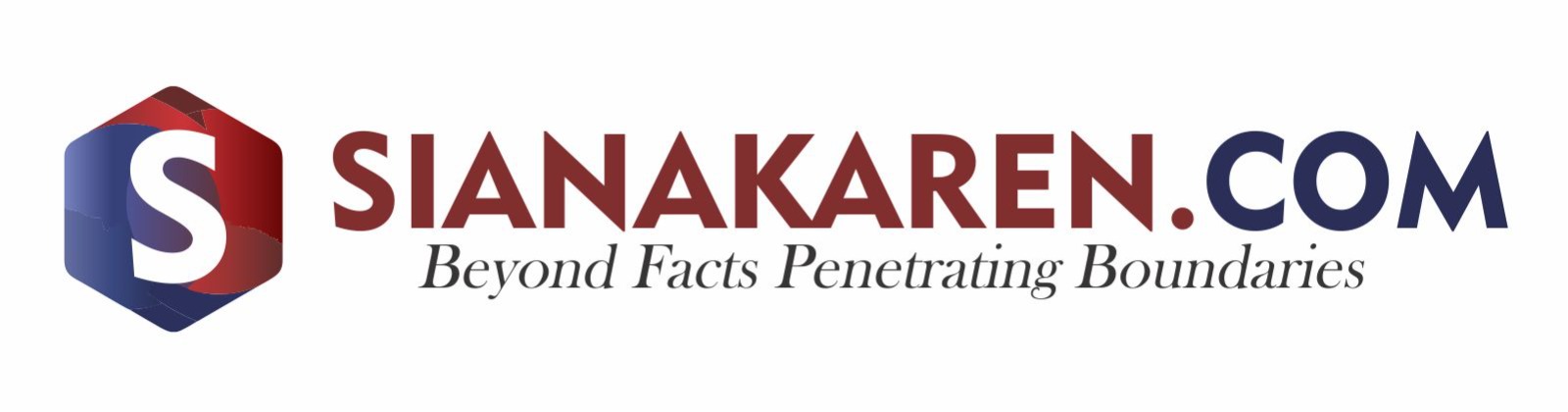
COMMENTS