Dengan segala fenomena dan kondisi demokrasi politik Indonesia saat ini, agaknya populisme Jokowi mesti bergerak lebih dari sekedar blusukan.
 |
| Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam debat publik menjelang Pilpres 2019. Foto: Dok. Istimewa. |
Dengan segala fenomena dan kondisi
demokrasi politik Indonesia saat ini, agaknya populisme Jokowi mesti bergerak lebih
dari sekedar blusukan.
Patut
diterima fakta bahwa kemunculan Jokowi persis ketika sistem politik dan ekonomi
bangsa kita sedang dalam keadaan “terancam”. Menguatnya pakta oligarkis,
mandulnya sistem perwakilan, karakter elitisme pejabat publik, birokratisme,
dan bangkitnya politik massa (mobokrasi)
turut merongrong upaya demokratisasi pasca angin segar Reformasi (1998). Di
tengah kondisi demikian, ketidakpercayaan dan ketidakpuasan rakyat terhadap
lembaga-lembaga politik formal menjadi niscaya. Namun, alih-alih membawa “obor
promotheus” ke bumi Nusantara, Jokowi kini terbentur oleh real-poilitik
primordial yang masif.
Sejak
terpilih menjadi Presiden di Pilpres 2014, memang ada banyak perubahan terjadi:
pembangunan infrastruktur besar-besaran di kota dan pedesaan, perbaikan ekonomi
rakyat, reorganisasi fiskal, dan sedikit keberhasilan dalam program
redistribusi kemakmuran. Jokowi juga secara perlahan berupaya merestrukturisasi
dominasi oligarkis di tubuh pemerintahan. Sistem birokrasi yang elitis berubah
menjadi lebih populis. Filosofi seorang rocker
yang bekerja cepat-tepat dan logika pasar pun diterapkan.
Namun pertama-tama, “fenomena populisme
yang tercermin pada sosok Jokowi, janganlah terlalu cepat dikatakan sebagai
sejenis perubahan,” demikian tulis Max Lane (dalam AE Priyono dan Usman Hamid (eds.): 2015, 823-845).
Menurutnya, apa yang terjadi dengan gaya politik Jokowi hanya menunjukkan bahwa
ada hubungan ke arah proses perubahan tersebut. Proses perubahan tersebut
adalah bahwa Jokowi sebagai pengusaha lokal di Solo bisa meraih kursi
kepresidenan, meski ia bukanlah politisi atau kader partai. Ini menunjukkan gejala
baru demokratisasi di Indonesia, bahwa seorang pengusaha atau politisi lokal
dapat meraih kesempatan menduduki jabatan tertinggi di negeri ini.
Lane
melihat ada tiga poin kunci kesuksesan Jokowi. Pertama, Jokowi
berhasil membaca kebencian masyarakat luas
terhadap gaya elitisme, yang merupakan
kecenderungan umum para politisi dan pejabat publik, sehingga ia memilih blusukan. Kedua, selama menjabat sebagai pejabat publik, Jokowi tidak
tersangkut masalah korupsi. Dan ketiga,
Jokowi secara konsisten menerapkan kebijakan redistribusi kesejahteraan (social safety net), antara lain lewat Kartu
Sakti: KIP, KIS dan KKS. Kebijakan ini menjadi senjata andalannya
dalam kampanye politiknya hingga meraih kekuasaan sebagai Presiden.
Setelah
menahkodai bangsa Indonesia selama kurang lebih empat tahun, Jokowi kini
dihadapkan pada situasi “krusial”, yang mana harus memilih calon Wakil Presiden
(wapres) yang “cocok” menurut kacamata seluruh komponen masyarakat Indonesia.
Kenapa? Karena bila salah memilih calon wakil presiden yang tepat, itu akan
berpotensi rentan terhadap posisi dan elektabilitasnya akibat guncangan politik
oposisi. Maka tidak terlalu berlebihan bila partai koalisi memandatkan
sepenuhnya keterpilihan wapres kepadanya. Hal itu agak bertolak belakang dengan
koalisi partai oposisi, di mana masing-masing partai pengusung menyiapkan
kadernya untuk dipilih oleh Prabowo.
Pada
Kamis (9/8), secara mengejutkan Jokowi telah menjatuhkan pilihan secara purna cawapresnya
pada sosok senior ulama, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin. Sementara Prabowo pun di
luar ekspektasi partai koalisi malah memilih Sandiago Uno, Wakil Gubernur DKI
Jakarta saat ini. Penetapan cawapres kedua kubu itu persis sehari sebelum
penutupan bursa pendaftaran capres-cawapres di Pilpres 2019.
Menyimak
fenomena politik aktual saat ini, agaknya gaya politik populisme Jokowi sebagaimana
dijalankan pada Pilpres 2014 lalu tidak lagi relevan. Gaya politik blusukan dengan merendam diri di lumpur,
atau menyapa rakyat di pasar, tidak lagi dibutuhkan. Memang karakter
kepemimpinan demikian yang diharapkan rakyat, karena sesuai dengan makna
pemimpin sebagai pelayan masyarakat. Tapi de
facto, justru tipe pemimpin seperti itu yang dikritik oposisi dengan alasan
yang sangat kerdil: ‘Indonesia butuh pemimpin tegas’.
Inilah
fakta bahwa budaya dan moralitas politik kita bergerak pada rel yang sangat
kontraproduktif. Bahwa saat ini bangsa kita sedang tidak membutuhkan pemimpin
yang bersih, tapi pemimpin yang mampu mengartikulasi kepentingan
ekonomi-politik segelintir orang; pemimpin yang justru muncul dari rahim
oligarki dan korup.
Karena
itu, pasca penetapan capres-cawapres Pilpres 2019, Jokowi diharapkan mampu
mengkonsolidasi kekuatan politik, bukan hanya dengan blusukan, tapi juga dengan menjalin komunikasi politik yang cerdas
di antara sesama elit politik. Apa yang telah dilakukannya pada akhir tahun
2016 dan awal tahun 2017 pasca Demo 212,
menunjukkan kepiawaiannya menyusun kekuatan politik. Dengan menyambangi para
elit partai, pemimpin agama dan organisasi massa, Jokowi perlahan-lahan
merancang basis politiknya agar tetap kuat dan menjadi figur sentral dalam
percaturan politik nasional.
Hal
itu nyata, bahwa hingga saat ini, tidak ada satu pun tokoh nasional yang mampu
mengikis kepopulerannya. Bahkan, pada perhelatan demokrasi (Pilpres) dua kali beruntun,
Jokowi menjelma sebagai salah satu tokoh yang sulit digoyang, kecuali lewat
praktik-praktik subversif yang kerdil dari lawan-lawannya.
Penunjukkan
cawapres terhadap tokoh agama, Ma’ruf Amin, janganlah cepat-cepat dilihat sekedar
untuk kepentingan pragmatis, tapi bisa dilihat sebagai kemajuan etis politik
kebangsaan, bahwa politik ulama pun punya tempat yang relevan di republik ini
demi konsolidasi politik. Sebab, konsolidasi politik inilah yang menjadi
pekerjaan sulit sebuah negara yang merdeka akibat pertumpahan darah seperti
Indonesia (bdk. Huntington: 1995, 347-354).
Kini
sudah semestinya populisme Jokowi bergerak pada rel yang tidak biasa. Di satu
sisi, ia mesti tetap menjaring kekuatan dengan masyarakat akar rumput (blusukan), tapi di sisi lain, ia juga
mesti mengakomodasi “terjangan” politik horizontal demi tercapainya agenda
pembangunan Revolusi Mental dan Nawacita.
Sebab untuk melembagakan agenda populis ia memerlukan konsolidasi politik tingkat tinggi, apalagi
ketika representasi (DPR) melemah dan kehilangan kredibilitas. Lebih
dari itu, transformasi program
populis ke agenda publik mengandaikan keberfungsian semua elemen dan institusi
demokrasi.*
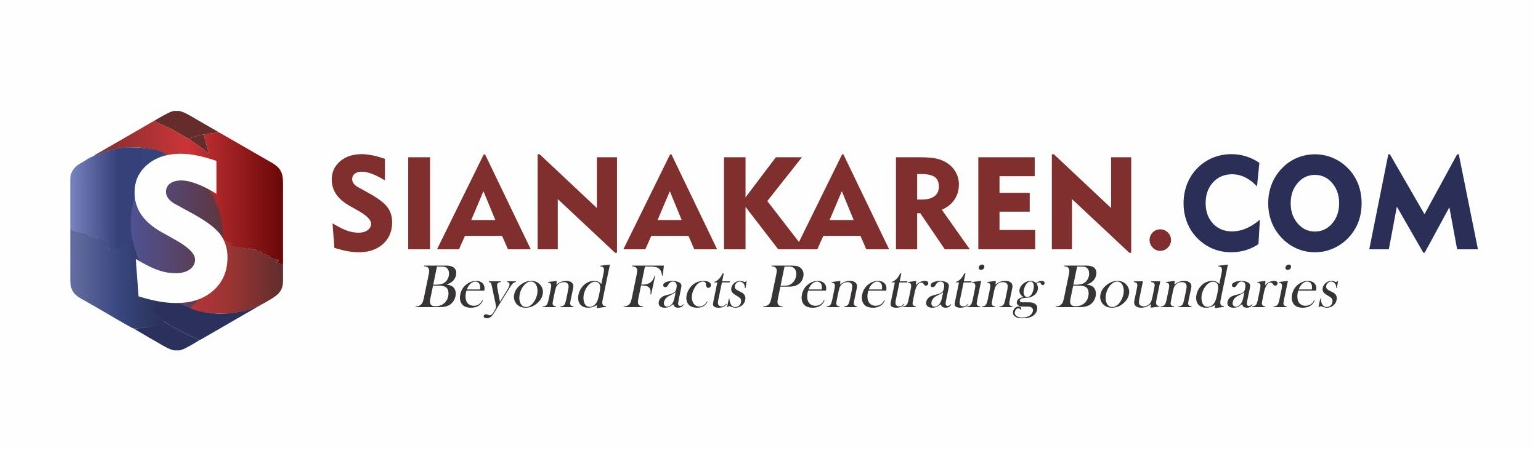











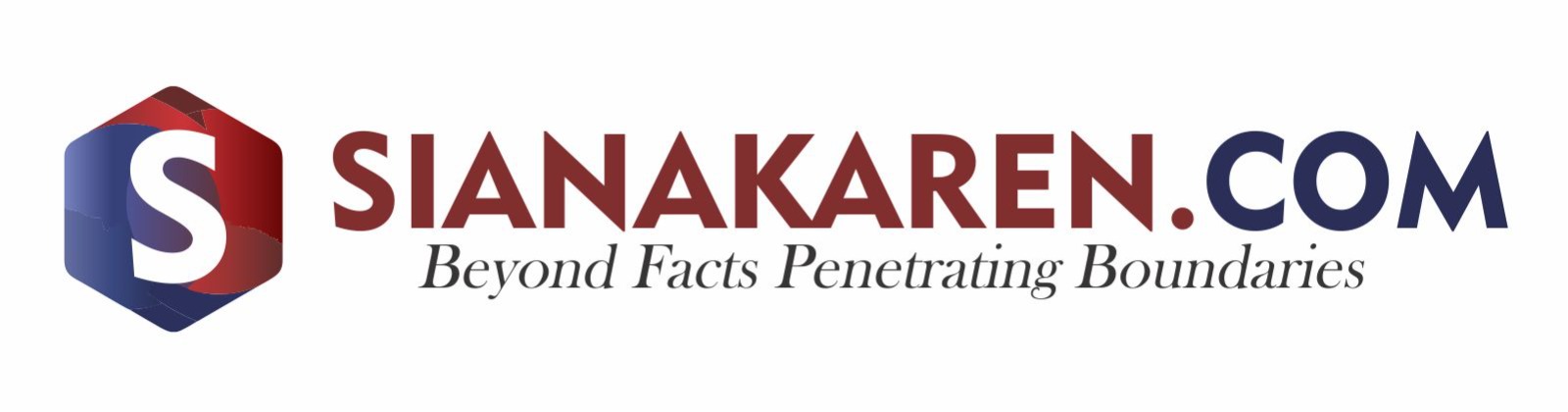
COMMENTS