Temuan survei yang dilakukan atas kerja sama Universitas Gajah Mada dan University of Oslo menyatakan bahwa demokrasi Indonesia mulai mengarah pada munculnya populisme meskipun ia tidak bersifat ideologis.
 |
| Ilustrasi kebebasan berdemokrasi. Kredit: Uniqpos.com |
Temuan survei yang dilakukan atas kerja
sama Universitas Gajah Mada dan University of Oslo (2014) menyatakan bahwa
demokrasi Indonesia mulai mengarah pada munculnya populisme meskipun ia tidak bersifat ideologis (Bdk. Pratikno and Lay,
2013).
Hasil penelitian
tersebut beriringan dengan munculnya Jokowi ke pentas politik nasional,
serentak terpilihnya Jokowi menjadi Presiden di tahun 2014. Demokrasi
yang semula dipenuhi oleh aktor dominan (elitisme)
bergeser kepada tampilnya aktor-aktor politik alternatif, atau biasa disebut
sebagai “politik luar”. Dengan itu relasi
kekuasaan pun berubah. Dari yang semula
semata menjadi milik kaum
elite, kini menjadi milik masyarakat warga (civil society).
Fenomena politik
populisme memang merupakan sesuatu yang relatif baru dalam ranah analisis dan
praktik politik
kontemporer. Ada pelbagai perspektif teori
untuk memahami populisme, baik dari teori politik, sosial, dan maupun teori kelas.
Jadi patut diakui bahwa pemahaman kita akan populisme akan sangat luas dan
lebar.
Namun salah satu pandangan teoretis paling komprehensif dikemukakan oleh teoretisi asal
Argentina, Ernesto
Laclau. Laclau (1997) memahami populisme sebagai gerakan politik multi-kelas dan
supra-kelas yang hadir dalam momen politik rapuhnya hegemonik kekuatan politik
dominan yang memberi munculnya struktur kesempatan politik baru bagi tampilnya
gerakan politik akar rumput yang dipimpin oleh pemimpin kharismatik untuk
mengartikulasikan wacana anti-kemapanan.
Menurutnya,
populisme sendiri dipahami dalam dua konteks yang berbeda, yaitu: 1) secara
struktural terkait dengan kondisi momen-momen krisis struktural ekonomi dan
krisis institusi politik, dan 2) populisme sebagai sebuah diskursus yang
menghubungkan setiap elemen dari gerakan sosial dan politik yang terlibat di
dalamnya.
Sebagai
sebuah diskursus terbuka, ekspresi gerakan politik populisme bisa
termanifestasi dalam ekspresi politik sayap Kanan, Tengah maupun Kiri,
tergantung dari perimbangan kekuatan sosial dalam arena politik di suatu negara
dalam kondisi spesifik yang memunculkannya.
Jadi secara sederhana, populisme gerakan politik akar rumput untuk melawan
dominasi kekuasaan elit politik yang korup, neoliberalisme, dan kapitalisme.
Dalam konteks
politik Indonesia, sejak awal kemerdekaan, mendiang Soekarno, melalui ideologi
politik marhaenisme,
secara implisit telah mewacanakan gaya politik tersebut. Untuk tidak dikatakan
sebagai pemimpin populis, Soekarno cenderung melakukan pendekatan kebijakan
pro-rakyat kecil dan budaya gotong-royong.
Namun bentuk dan karakter pemimpin
populis paling mutakhir terpampang pada figur Jokowi, Fadel Muhammad, Ahok, Ridwan Kamil,
dan Tri Rismaharini serta masih banyak lagi. Lantas, mungkinkah populisme telah mengubah arah
perpolitikan Indonesia, yang setelah
satu setengah dekade, “angin”
Reformasi masih tetap dibalut
pakta oligarkis dan “antek-antek”
Soeharto.
Secara gamblang
kenyataan menunjukkan signifikansi perubahan paradigma
tersebut justru ketika
pemimpin-pemimpin populis tingkat lokal mampu mendesain wacana atau isu kesejahteraan menjadi
kebijakan publik yang makin terasa manfaat dan menujukkan kemajuan. Eric Hiariej (2016) mengamini perubahan tersebut. Bahwa telah
terjadi pergeseran paradigma demokrasi, yaitu
dari bureaucratic polity kepada bureaucratic populist yang menekankan pentingnya dukungan publik dalam sebuah
kebijakan.
Deretan pemimpin populis di
atas ternyata mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
di daerahnya. Lihat saja Jokowi ketika memimpin kota Solo dan DKI Jakarta,
berikut Ahok di Belitung Timur dan DKI Jakarta, Fadel di provinsi Gorontalo,
Ridwan Kamil di kota Bandung, dan Tri Rismaharini di kota Surabaya, serta
beberapa pemimpin lokal lain yang telah berhasil mem-politisasi kebijakan populis di daerahnya.
Mengikuti paradigma Hiariej,
benar bahwa mereka telah berhasil menciptakan budaya birokrasi yang populis, yaitu
birokrasi yang benar-benar melayani dan berpihak pada rakyat.
Chris Rohmann
(1999) memberikan berbagai label atas demokrasi. Salah satu dari lima kategori tersebut
adalah demokrasi populis. Menurutnya, demokrasi populis menekankan pada
pemerintahan yang mandiri oleh orang-orang bebas dan sederajat, melihat
pemerintah sebagai ekspresi dari “kehendak rakyat”, dan dengan demikian
berusaha untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat.
Hal-hal tersebut
dapat dilakukan, baik secara elektoral maupun dengan cara-cara non-elektoral,
karena mereka mengakui bahwa hasil pemilihan (Pemilu) tidak selalu mencerminkan
kehendak rakyat.
Hal ini senada dengan pandangan
Habermas, bahwa demokrasi tidak ditentukan oleh Pemilu, tetapi masa di antara
kedua Pemilu.
Di lain pihak,
Robert A. Dahl (1956) mengemukakan bahwa demokrasi populis adalah bentuk protes
terhadap semua keterkekangan liberalisme, sekaligus memberikan perlawanan keras
terhadap tirani mayoritas yang mengabaikan atau menolak ha-hak minoritas.
Pengertian ini
sebenarnya mirip dengan apa yang didefenisikan Habermas tentang demokrasi
deliberatif-nya. Bahwa ideal demokrasi terjadi ketika masyarakat secara aktif
mengambil bagian dalam sebuah wahana
diskursus untuk menentukan nasib dan kehendaknya.
Dengan kata lain,
demokrasi populis lebih condong ke arah demokrasi langsung, di mana rakyat,
tanpa melalui lembaga representasi formal, membuat keputusan sendiri tentang
permasalahan publik yang dihadapinya.
Di dalam diskursus
tersebut terhubunglah kepentingan orang-orang yang bebas dan sederajat, tanpa
memarginalisasikan individu lain, sehingga keputusan dan kebijakan yang
dihasilkan sungguh-sungguh mencerminkan kehendak dan kepentingan bersama.
Kebebasan dan
kesederajatan diperoleh atau dilegitimasi melalui pengakuan pihak lain yang
menghargai faktum keberagaman pendapat, kepentingan, akses, dan kapasitas
pengetahuan. Tanpa pengakuan, diskursus dalam forum bersama tersebut tidak
mungkin mencapai konsensus.
Dengan demikian, ada keterkaitan
substantif antara demokrasi populis, demokrasi deliberatif, dan demokrasi
langsung. Ketiganya sama-sama mengutamakan partisipasi dan pengaruh rakyat
dalam penentuan arah kebijakan publik. Di dalamnya ada “pertarungan” wacana
yang melibatkan rakyat secara langsung untuk mengelola sumber-sumber daya dan
melakukan kontrol atas kesejahteraan.
Namun yang khas dari demokrasi
populis adalah bahwa ia tidak hanya
menyadarkan aktor politik untuk bertindak “atas nama” rakyat, melainkan juga
membuka peluang dan akses untuk mendeliberasi kebijakan publik. Sejauh negara
dan pemerintah bisa menciptakan sistem dan lembaga yang populis, sejauh itu
pula proses demokratisasi tercipta.
Fakta bahwa menguat dan suksesnya
politik populisme di beberapa daerah/kota menunjukkan demokrasi pada hakekatnya
bersifat populis. Untuk tidak
dikatakan sebagai perubahan, bukti empiris tata pemerintahan birokrasi berciri
populis di beberapa daerah justru memperkuat asumsi publik, bahwa sesungguhnya
demokrasi Indonesia pasca-Reformasi mengarah kepada demokrasi populis.
Mau tidak mau, suka tidak suka,
fakta bahwa strategi populisme justru mampu mengubah budaya politik yang kotor
warisan Orde Baru, mesti dirayakan dan diterima secara proporsional ke dalam
sistem politik baru Indonesia yang lebih terbuka dan bebas.
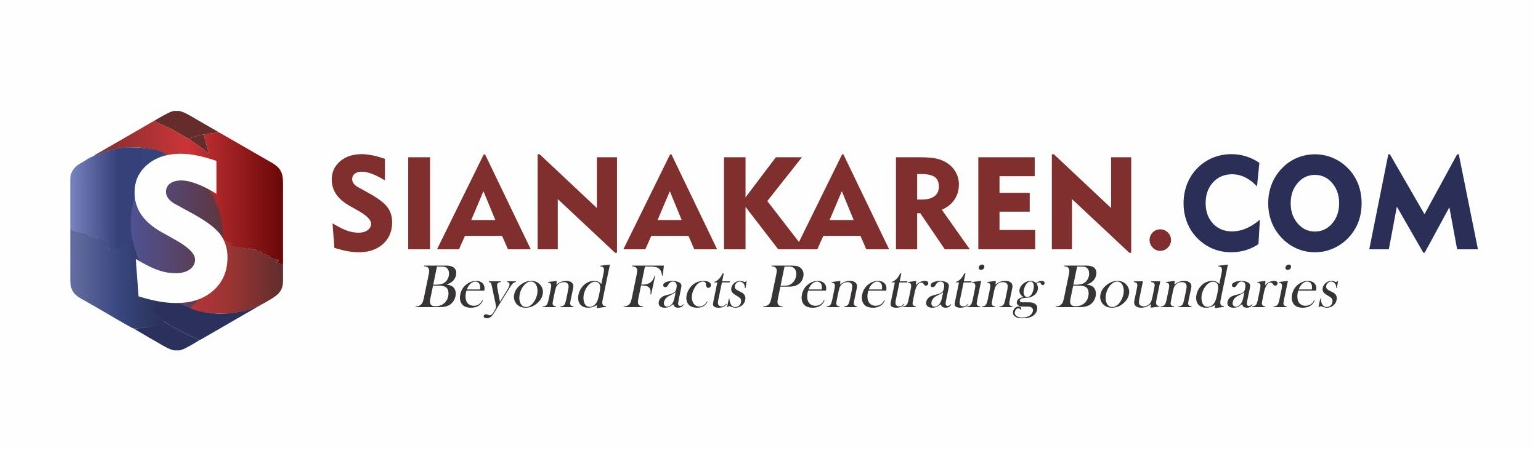











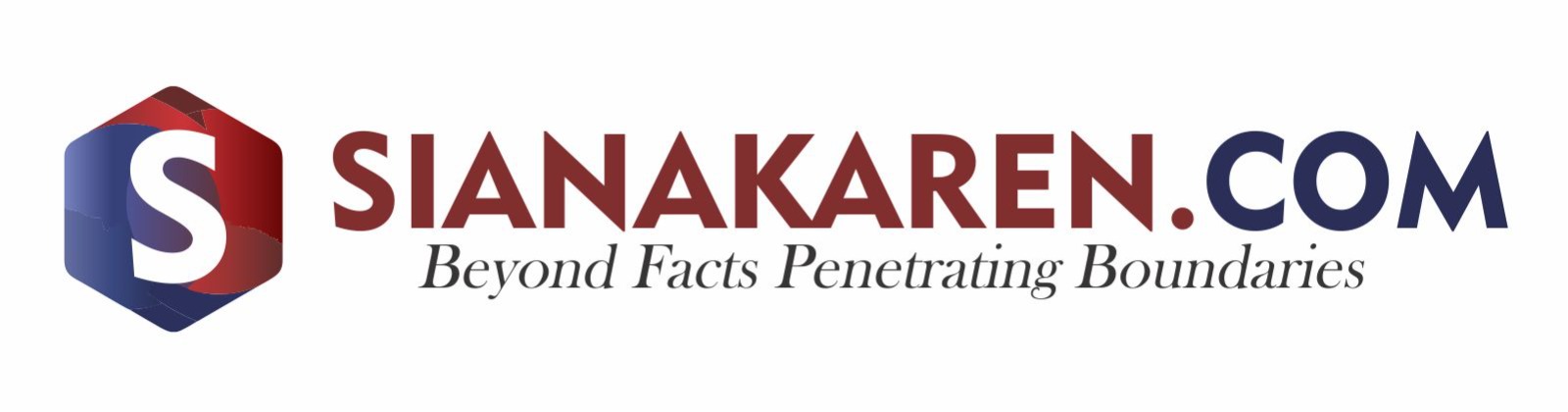
COMMENTS